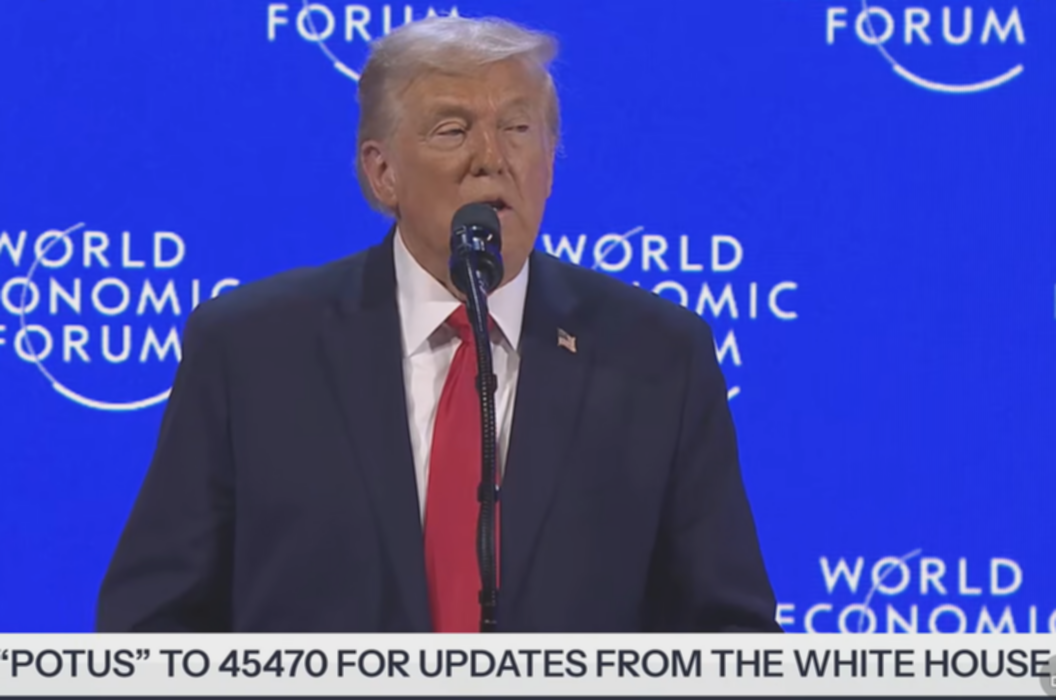Madagaskar Memanas: Tentara Turun ke Jalan, Presiden Tuduh Kudeta!

Krisis politik di Madagaskar semakin memanas setelah beberapa kelompok tentara bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah di ibu kota, Antananarivo. Demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Andry Rajoelina ini terus mendapatkan momentum, menghadirkan tantangan paling serius bagi pemerintahannya sejak terpilih kembali pada tahun 2023.
Menanggapi eskalasi ini, Kepresidenan Madagaskar pada Minggu (12/10) mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut gelombang protes tersebut sebagai upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan paksa. Gerakan yang dipimpin oleh pemuda ini, yang dimulai pada 25 September, berhasil mengumpulkan massa besar di Lapangan 13 Mei Antananarivo pada Sabtu (11/10). Uniknya, inspirasi protes ini datang dari “Gerakan Gen Z” yang sebelumnya terjadi di Kenya dan Nepal.
Pusat dari pergeseran loyalitas ini adalah unit elit militer CAPSAT. Pada pertemuan di salah satu barak di pinggiran kota, anggota CAPSAT terang-terangan menyerukan solidaritas terhadap para demonstran yang menuntut Andry Rajoelina mundur. Seruan ini memiliki bobot sejarah, mengingat pasukan CAPSAT justru berperan penting membantu Rajoelina merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2009.
Dalam video yang viral di media sosial, prajurit CAPSAT dari pangkalan distrik Soanierana mendesak seluruh tentara, polisi, dan aparat penegak hukum untuk bersatu. Mereka secara tegas menolak perintah menembak warga sipil, menyerukan agar tidak mematuhi atasan yang memerintahkan kekerasan, bahkan menyarankan untuk mengarahkan senjata kepada para komandan tersebut. Selain itu, mereka juga menginstruksikan personel militer di bandara untuk melarang semua penerbangan lepas landas dan meminta pasukan di kamp-kamp lain untuk menolak menembak para pengunjuk rasa, sembari menunggu instruksi lebih lanjut.
Pada saat yang sama, polisi berupaya membubarkan demonstran menggunakan granat kejut dan gas air mata. Namun, rekaman video dari media lokal menunjukkan pemandangan dramatis: beberapa tentara terlihat meninggalkan barak mereka untuk mengawal para pengunjuk rasa menuju Lapangan 13 Mei, memperkuat solidaritas militer-sipil. Demonstrasi pada Sabtu (11/10) ini menjadi yang terbesar sejauh ini, dipicu oleh kemarahan publik terhadap kekurangan listrik dan air yang telah berlangsung lama.
Merespons situasi yang memanas, Menteri Angkatan Bersenjata Madagaskar yang baru dilantik, Jenderal Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, menyerukan agar para prajurit tetap tenang. Dalam konferensi pers, ia menekankan pentingnya dialog dan menyatakan bahwa Tentara Madagaskar harus tetap menjadi mediator serta garis pertahanan terakhir bangsa.
Aksi represif aparat keamanan sebelumnya juga telah menimbulkan korban. Pada Kamis (9/10), beberapa orang terluka saat pasukan keamanan membubarkan pengunjuk rasa menggunakan gas air mata, peluru karet, dan kendaraan lapis baja. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tergeletak tak sadarkan diri setelah dikejar dan dipukuli aparat menjadi viral di media sosial, dan insiden ini bahkan disaksikan oleh wartawan AFP. Mengkhawatirkan situasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (10/10) mendesak pihak berwenang untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan menjunjung tinggi hak berserikat serta berkumpul secara damai. Menurut PBB, setidaknya 22 orang tewas dan 100 lainnya terluka. Namun, Presiden Rajoelina membantah angka tersebut, menyatakan pada Rabu (8/10) bahwa hanya 12 korban jiwa yang terkonfirmasi, dan ia mengklaim semua korban adalah penjarah serta pelaku vandalisme.
Pada awalnya, Presiden Rajoelina mencoba meredakan ketegangan dengan mengambil sikap lebih damai, bahkan memecat seluruh menterinya sebagai respons atas gelombang protes. Namun, pendekatan ini segera bergeser. Pada Senin, ia menunjuk perwira militer Ruphin Fortunat Zafisambo sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet baru yang sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan angkatan bersenjata, keamanan publik, dan kepolisian, menandakan konsolidasi kekuatan militer dalam pemerintahannya.
Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Madagaskar memang memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik dan pemberontakan rakyat sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Momen krusial terjadi pada tahun 2009 ketika protes massal memaksa Presiden Marc Ravalomanana mundur, dan militer kemudian mengangkat Andry Rajoelina ke tampuk kekuasaan untuk periode pertamanya. Setelah itu, ia memenangkan pemilihan ulang pada 2018 dan kembali pada 2023, meskipun pemilu terakhir tersebut diwarnai boikot dari pihak oposisi, menambah kompleksitas krisis politik yang kini dihadapinya.
Ringkasan
Krisis politik di Madagaskar memanas setelah ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah menuntut pengunduran diri Presiden Andry Rajoelina, yang dituduh presiden sebagai upaya perebutan kekuasaan ilegal. Situasi semakin genting dengan bergabungnya beberapa kelompok tentara, termasuk unit elit CAPSAT, yang menyatakan solidaritas dengan demonstran dan menolak menembak warga sipil. Pergeseran loyalitas CAPSAT ini memiliki bobot historis karena unit tersebut membantu Rajoelina merebut kekuasaan pada kudeta tahun 2009.
Pemerintah berupaya membubarkan demonstrasi yang dipicu oleh kemarahan publik atas kekurangan listrik dan air, menggunakan gas air mata yang mengakibatkan korban luka dan tewas, namun Presiden membantah angka tersebut. Menanggapi situasi ini, Presiden Rajoelina menunjuk perdana menteri baru dan membentuk kabinet yang didominasi oleh kalangan militer dan keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pihak berwenang menghentikan kekerasan tidak perlu, mengingat Madagaskar memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik.